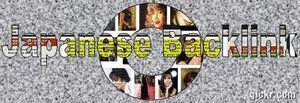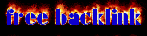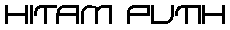Hanya ada dua profesi di dunia, yaitu guru dan bukan guru. Mungkin ini hanya sebuah pandangan subjektif, meskipun mungkin juga hal ini pun sangat benar adanya. Profesi guru menghasikan profesi lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Ada sebagian orang yang jalan hidupnya berubah karena diinspirasi sosok guru. Guru, tak cukup pandai menjelaskan sajian materi pelajaran, tetapi lebih dari itu, guru adalah orang yang mampu membuat perbedaan bagi pribadi-pribadi siswanya karena perilakunya yang layak digugu dan ditiru.
Jika kita cermati sejarah perkembangan profesi guru di tahun 1960-an, profesi guru masih menjadi suatu profesi yang banyak diminati sehingga proses seleksinya pun relatif ketat. Alhasil, pada saat itu, mereka yang diterima untuk bisa belajar di lembaga pendidikan guru adalah para lulusan terbaik dari sekolah menengah (ranking I sampai III).
Siahaan, S. (2009), memiliki analisis tersendiri tentang fakta empiris terjaminnya kualitas mutu proses pendidikan guru di saat itu, di antaranya (1) lembaga pendidikan guru menerima peserta didik yang prestasi belajarnya termasuk dalam peringkat 3 besar, (2) selama mengikuti pendidikan guru, para peserta didik mendapat beasiswa atau tunjangan ikatan dinas, (3) selama mengikuti pendidikan guru, para peserta didik diasramakan sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber belajar yang tersedia, dan (4) setelah menyelesaikan pendidikan keguruan, mereka langsung ditempatkan sebagai guru di daerah asalnya masing-masing.
Satu lagi yang tak boleh dilupakan, di era tahun 1960-an, profesi guru tidak hanya dianggap prestisius di negeri sendiri, tapi diapresiasi juga oleh negara tetangga kita, Malaysia. Pemerintah Malaysia pada saat itu melihat para guru di Indonesia sebagai sosok yang memenuhi kualifikasi mereka untuk mengajar di Malaysia. Wajar jika kemudian mereka “mengimpor” guru-guru Indonesia untuk mengajar di Malaysia, serta “mengekspor” guru-guru mereka untuk mengikuti pendidikan guru di Indonesia. Era keemasan profesi guru di masa lampau.
Sampai di masa Orde Baru, profesi guru mengalami fase kemunduran. Tidak semua lulusan lembaga pendidikan guru memutuskan pilihan hidupnya sebagai guru. Terlebih ada juga sebagian lulusan lembaga pendidikan guru yang diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) tetapi tidak bekerja sebagai guru. Nyatanya, kondisi ini dipicu oleh persepsi yang berkembang mengenai situasi kekinian terkait dengan profesi guru, di antaranya: (1) gaji guru yang relatif rendah, (2) rumitnya prosedur birokrasi yang harus dihadapi guru dalam pengembangan karirnya, (3) merosotnya status guru di tengah-tengah masyarakat (Suparman, 2006). Akibatnya, lembaga pendidikan guru menjadi sangat sulit untuk mendapatkan lulusan sekolah menengah atas yang berprestasi dan memiliki keminatan menjadi guru. Tak dapat disangkal lagi, inilah sebab utama rendahnya ketersediaan guru-guru profesional di Bumi Pertiwi.
Terlebih, reposisi peran dan tanggung jawab lembaga pendidikan guru yang terus berkembang turut berpengaruh dalam menyiapkan profil guru yang berkualitas. Pendidikan Tenaga Penghasil Guru (PTPG), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP), Institut Pendidikan Guru (IPG), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), dan sekarang menjadi Universitas Pendidikan (Universitas Mantan IKIP, seperti Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Malang, dsb) merupakan proses transformasi dari lembaga pendidikan guru untuk menjawab kebutuhan penyediaan tenaga guru yang profesional dan berkarakter. Sayang seribu sayang, ketika tingkat kesejahteraan guru masih berada pada posisi yang relatif rendah, ini menjadi pemicu rendahnya minat para generasi muda untuk menjadi guru. Alasannya sangat sederhana, bekerja menjadi guru tidak menjamin penghidupan yang lebih baik. Wajar jika kemudian kita menemui fakta di lapangan bahwa sebagian besar orang memutuskan hidup menjadi guru hanya sebagai pilihan hidup yang kedua, ketiga, bahkan mungkin yang terakhir. Sungguh ironis.
Kini, pascaberlakunya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi guru terkesan sedang diperhatikan dan hendak diangkat harkat martabatnya. Di sisi lain, kita malah makin mengkhawatirkan hadirnya banyak oknum yang mengaku guru dan tiba-tiba berubah pikiran untuk menjadi guru karena alasan yang satu ini. Segala cara dihalalkan. Pemalsuan sertifikat kian marak, satu dari sekian kasus curang yang dilakukan oknum guru yang tanpa sadar hendak menghancurkan nama baik korpsnya guru. Semua dilakukan semata untuk mendapatkan kenaikan upah satu kali gaji pokok, bukan atas dasar profesionalisme. Jika cara ini tidak diimbangi dengan upaya penguatan kapasitas lembaga pendidikan guru dan penataan sistem pengembangan profesional guru secara sistematis-berkelanjutan, kebijakan populer ini dirasa tak akan mampu menguatkan citra profesi guru di masyarakat. Yang ada malah kita sedang giat memproduksi musang berbulu domba, yaitu orang yang menjadikan profesi guru sebagai batu loncatan untuk mendapatkan kekayaan materi dunia, bukan orang yang menjadikan kekayaan dunia sebagai alat untuk menyempurnakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Ini perkara yang patut dicermati seksama.
Jika kita mau belajar dari sejarah masa lampau, profesi guru hanya akan menjadi terhormat ketika pemerintah mau dan mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memuliakan profesi mereka. Menurut Dedi Supriadi dalam bukunya Mengangkat Citra dan Martabat Guru (1999), berdasar berbagai studi yang dilakukan, tingkat kesejahteraan merupakan penentu yang amat penting bagi kinerja guru dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jangan sampai perbaikan kesejahteraan bagi guru hanya untuk mengakomodasi kepentingan politis semata. Namun, langkah itu harus menjadi bagian dari proses pengembangan profesionalisme guru secara utuh.
Dua hal lain yang tak boleh dilupa, lakukan seleksi yang superketat bagi mereka yang hendak menjadi guru dengan memperhatikan aspek kemampuan akademis dan keminatan. Satu langkah strategis lainnya adalah melakukan upaya pembenahan dan penguatan kapasitas lembaga pendidikan guru sebagai tempat pertama dan utama untuk membina kapasitas profesional sekaligus membina akhlak karimah bagi para calon guru. Jika dua upaya ini tidak dilakukan, sesungguhnya kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk menempatkan profesi guru pada singgasana yang terhormat.
( Lampung Post).